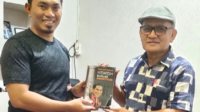Oleh: Afiq Naufal
(Presiden Mahasiswa Univ. Paramadina dimasanya/Mahasiswa Parepare)
Ada satu momen yang bikin saya terdiam: ketika Prabowo berkata, “Ngurus republik ini ternyata rumit… tapi saya tetap semangat.”
Bukan soal semangatnya. Tapi soal kejujuran yang akhirnya telontar keluar setelah sekian tahun pidato berapi-api.
Kejujuran yang terdengar lebih jujur dari 21 tahun janji reformasi, atau bahkan 10 tahun diam-diamnya Jokowi.
Ucapan itu seperti anak muda yang baru sadar, ternyata pacaran itu nggak cuma soal bunga dan coklat, tapi juga tentang kompromi mood swing, biaya skincare, dan pertanyaan eksistensial tiap malam minggu.
Prabowo akhirnya tersedak. Bukan oleh lawan politik. Tapi oleh kompleksitas sistem yang tak bisa ditaklukkan dengan ketegasan belaka.
Demokrasi bukan barisan pasukan. Ia adalah pasar gagasan. Dan Prabowo, yang tumbuh dalam tradisi militer, kelihatan kebingungan seperti tentara disuruh ikut kelas tari balet.
Prabowo adalah anomali. Ia bicara soal menuntaskan kemiskinan, tapi lahir dari keluarga bangsawan ekonomi.
Ia bicara tentang supremasi sipil, tapi karir dan mentalitasnya terbentuk dari lorong-lorong militeristik.
Ia bicara tentang masa depan, tapi seringkali imajinasinya terdengar seperti kaset pita tahun 70-an.
Secara psikologis, kondisi ini disebut cognitive dissonance—ketika dua realitas bertabrakan dalam satu kepala.
Menurut Leon Festinger, individu akan cenderung menyelaraskan konflik batin itu lewat rasionalisasi atau perubahan sikap.
Dalam kasus Prabowo, konflik antara paradigma lama dan realitas baru inilah yang membuat kebijakannya sering terasa inkonsisten.
Kadang keras. Kadang lunak. Kadang “Ganyang koruptor!”
Kadang, “Ya udah deh, yang penting makan kenyang dulu.”
Masalahnya bukan pada ketidaksungguhan. Tapi pada ketidakmampuan untuk membaca zaman.
Prabowo adalah pria dengan cinta yang tulus pada negeri ini. Tapi tulus saja tidak cukup.
Karena demokrasi bukan hanya soal niat baik, tapi soal bagaimana niat itu dikomunikasikan.
Dan di sinilah masalahnya: komunikasi Prabowo cenderung maskulin, vertikal, dan satu arah.
Ia tidak sedang berbicara pada pasukan, tapi pada rakyat yang punya akses reply, retweet, dan komentar pedas.
Sementara demokrasi, seperti kata Cornelius Castoriadis, adalah “the institution of autonomy.”
Rakyat bukan obyek. Mereka adalah subyek politik.
Prabowo seringkali tampak seperti bapak keras yang ingin memberikan yang terbaik,
tapi menggunakan standar dan nilai dari masa lalu.
Padahal, anak-anak zaman sekarang ingin didengarkan dulu sebelum dinasihati.
Dan dunia, sayangnya, tidak lagi bisa dipimpin seperti barak militer.
Lalu, bagaimana ia bisa tersesat?
Demokrasi adalah labirin. Setiap tikungan adalah kompromi.
Setiap jalan buntu adalah negosiasi ulang.
Setiap pintu punya kuncinya sendiri—parlemen, oposisi, publik, dan algoritma sosial media.
Seseorang seperti Prabowo yang terbiasa dengan struktur komando seringkali akan frustrasi menghadapi sistem yang cair.
Ini bukan soal lemahnya karakter. Tapi tentang tidak cocoknya firmness dengan fluidity.
Jika memakai lensa Max Weber, kepemimpinan Prabowo awalnya dibingkai sebagai charismatic authority—pemimpin kuat yang digandrungi karena kharisma.
Namun dalam sistem demokrasi modern, yang dibutuhkan adalah transisi menuju legal-rational authority—di mana otoritas dibangun dari sistem, bukan dari persona.
Prabowo tampaknya masih berada di persimpangan ini.
Ia ingin dicintai sebagai tokoh revolusioner,
tapi dituntut bekerja seperti administrator negara.
Narasi besar tentang Prabowo sering dipenuhi ekspektasi ala film Marvel.
Pahlawan datang, mengganyang penjahat, lalu semua orang bahagia.
Tapi realitas politik Indonesia bukan dunia fiksi.
Korupsi tidak bisa diberantas hanya dengan gebrakan meja.
Kemiskinan tidak bisa dihapus dengan satu aplikasi.
Dan pembangunan tidak cukup dengan retorika makan siang gratis.
Yang dibutuhkan adalah perombakan struktural.
Mulai dari reformasi perpajakan, redistribusi aset, hingga penataan birokrasi yang tidak hanya gemuk tapi juga lambat.
Apakah Prabowo punya kapasitas ke situ?
Atau masih tersesat dalam romantisme populisme?
Lalu, di mana posisi rakyat?
Rakyat kini berada dalam dilema.
Mereka mendamba pemimpin tegas, tapi tidak ingin dibentak.
Mereka ingin perubahan cepat, tapi tidak ingin dilibatkan dalam proses panjang.
Ini adalah democratic paradox yang dikemukakan oleh Pierre Rosanvallon—demokrasi hari ini mengalami dilema antara kecepatan eksekusi dan legitimasi proses.
Pemimpin dituntut efisien, tapi juga harus partisipatif.
Dan dua hal ini seringkali bertabrakan.
Dalam konteks ini, Prabowo seolah menjadi korban dari ekspektasi zamannya sendiri.
Ia dijanjikan panggung yang megah, tapi ternyata panggung itu dipenuhi jebakan-jebakan etika, hukum, dan opini publik.
Setiap gerakannya diawasi.
Setiap ucapannya diulang-ulang, dibahas, direaksi.
Belum lagi tekanan dari pasar.
Investor tidak hanya membaca kebijakan.
Mereka membaca gestur.
Mereka membaca ekspresi.
Mereka membaca nada suara.
Itulah kenapa ketegasan Prabowo bisa mengubah niat baik menjadi sinyal bahaya.
Maka, jika benar Prabowo kini menyadari bahwa “mengurus republik ini rumit,”
itu seharusnya bukan dianggap sebagai kelemahan.
Tapi momen kesadaran.
Bahwa negara bukan medan perang.
Bahwa politik bukan soal menaklukkan, tapi merangkul.
Bahwa demokrasi bukan aritmatika hitam-putih,
tapi seni menavigasi nuansa.
Kalau dia mampu mengakui itu dan berubah,
mungkin dari labirin itu dia akan menemukan pintu keluarnya.
Tapi jika tidak, maka ia akan terus berputar-putar dalam jerat imajinasinya sendiri.
Demokrasi adalah panggung yang sulit.
Dan Prabowo, seperti tokoh dalam tragedi klasik Yunani,
sedang berjalan dalam labirin ciptaannya sendiri:
berisi bayangan kejayaan, cermin nostalgia, dan jalan buntu idealisme.
Mungkin yang ia butuhkan bukan penasihat militer.
Tapi seorang filsuf.
Atau pelatih tari.
Atau tukang komik.
Seseorang yang bisa memberitahu bahwa rakyat bukan pasukan.
Bahwa komunikasi adalah separuh dari kekuasaan.
Dan bahwa tersesat itu bukan akhir cerita—tapi kesadaran.