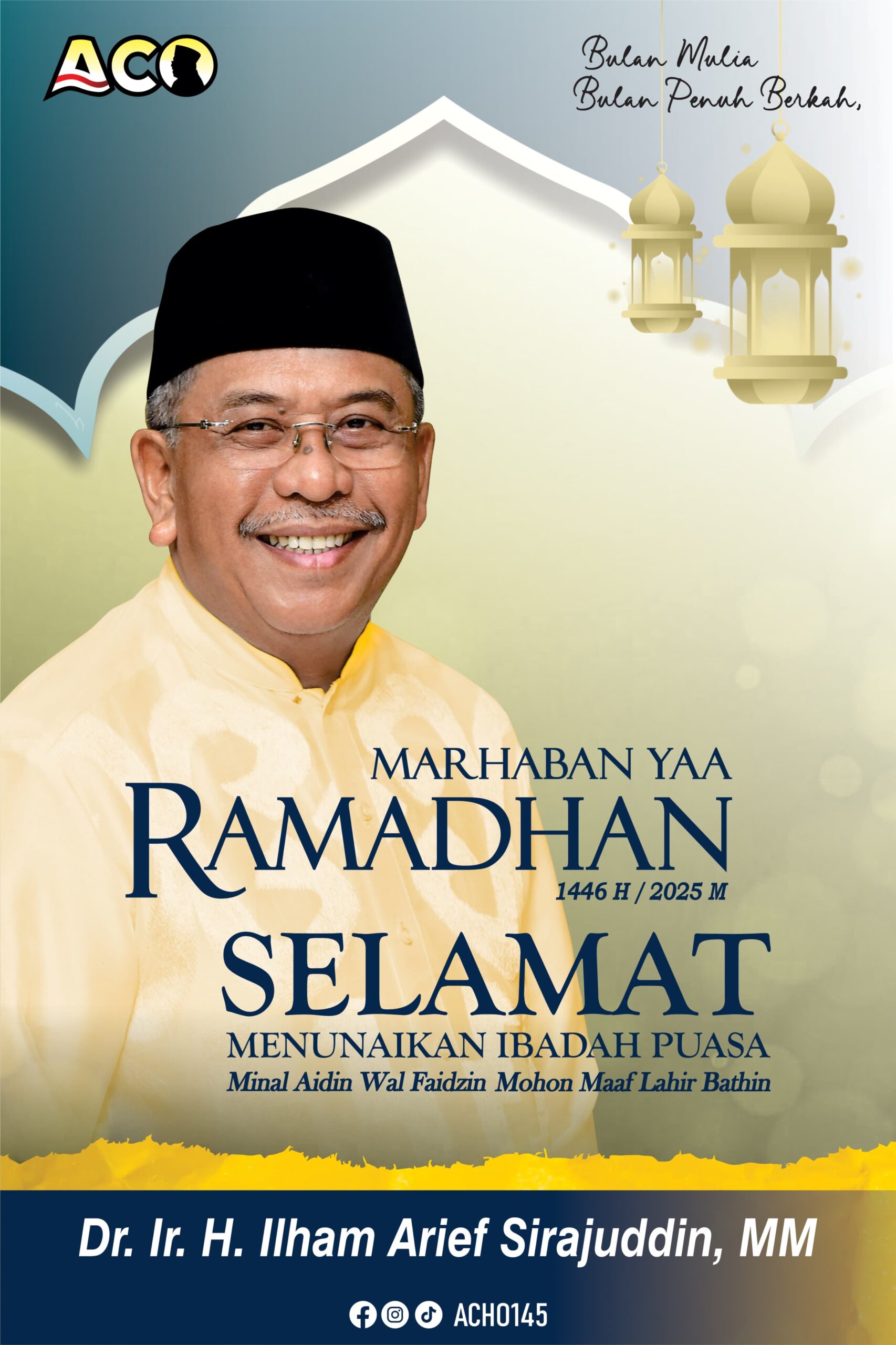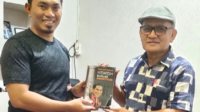Oleh : Mahrus Andis
Komunitas Pendukung Kedaulatan Budaya Sulawesi Selatan, diketuai Prof. Andi Halilintar Latief, melakukan dialog budaya bertajuk “Haji Bugis”.
Dialog yang berlangsung di aula Tribun Timur, Kamis 20 Maret 2025, menghadirkan dua akademisi selaku pembicara: Prof. Dr. Wahyudin Halim dan Prof. Dr. Idham Bodhi.
“Haji Bugis”, judul sebuah buku yang ditulis Dr. Syamsul Rijal Adhan, membahas berbagai dimensi dalam konteks pelaksanaan ibadah haji di kalangan masyarakat Bugis.
Sedianya dialog dimulai pkl. 16.00 wita namun baru berlangsung satu jam kemudian, hingga berakhir dengan buka puasa bersama.
Sebenarnya menarik pembahasan kedua pembicara tersebut. Sayang, waktu amat sempit untuk diskusi. Banyak nilai kearifan lokal ritual haji yang bisa diungkap di dalamnya.
Bahkan ada yang penting diluruskan, terutama dalam konteks pemahaman tradisional dan terminologi haji yang berkembang di masyarakat Sulawesi Selatan.
Bagi saya, ritualitas Haji Bugis tidak hanya bentuk pertemuan tiga dimensi; syariat, tradisi dan budaya modern, tapi sudah menjadi pengaruh besar yang melebur dalam praktek ibadah haji.
Hal ini penting diluruskan dengan pendekatan secara bijak. Tidak layak dilakukan pelarangan terhadap tradisi budaya yang sudah mengakar di masyarakat.
Janganlah mereduplikasi keputusan MUI Sulsel, tahun lalu, yang memfatwakan agar masyarakat tidak menyelenggarakan tradisi Maccèraq Tasiq karena dinilai bertentangan syariat Islam.
Padahal, tradisi tersebut hanyalah simbolisitas kesyukuran masyarakat nelayan atas rezeki hasil laut dari Tuhan.
Maccèraq Tasiq identik dengan tradisi Maccèraq Baca sebagai tanda syukur atas kekhataman 30 juz Al Quran.
Sesungguhnya, tradisi ritual ibadah haji atau Macceraq Tasiq bagi masyarakat Bugis adalah persoalan hati.
Projeksi niat ibadah di dalam hati kadang-kadang membutuhkan sentuhan budaya religius untuk meluruskan pemahaman tradisionalitas terhadap esensi akidah Islamiah.
Meluruskan pemahaman budaya agar tidak merusak tatanan syariat ibadah perlu ikhtiar secara kontinu.
Di sinilah peran para penyuluh dari Kementerian Agama yang, sejatinya membangun kolaborasi dengan budayawan Islam untuk meluruskan niat dan perilaku yang dinilai menyimpang dari syariat agama.
Di sisi lain, para ulama pun dituntut memahami gagasan pemikiran budaya lokal masyarakat dalam membangun relasi kehidupan beragama yang harmonis.
Artinya, masyarakat diarahkan melaksanakan ibadah haji sesuai syariat, sekaligus mereka dibimbing merefleksikan harapan-harapan religius (sennung-sennungeng) dalam konteks kepuasan batin beribadah di Tanah Suci.
Semiotika Haji Bugis harus jelas dipahami masyarakat Islam. Meskipun hanya terminologi kultural, namun hal semacam ini kadang-kadang terkesan menzalimi entitas keyakinan sekelompok umat Islam.
Salah satu contohnya adalah istilah Haji Bawakaraèng. Mereka yang melakukan ritual ibadah lebaran haji di puncak gunung Bawakaraèng dinilai menyalahi syariat Islam.
Padahal secara tradisi, hal itu hanyalah merupakan “sennung-sennungeng” (ekspresi harapan-harapan religius yang menjadikan puncak gunung sebagai ikonisitas tipografi tempat tertinggi) untuk berlebaran haji.
Haji Bawakaraèng bukan berarti bentuk pelaksanaan syariat “Ibadah Haji” melainkan hanya melakukan tradisi ritual “Lebaran Haji” (ingat: bedakan terminologi ibadah haji dengan lebaran haji).
Mereka menggelar lebaran haji di tempat yang dianggap menampung hikmah ketinggian/kemuliaan.
Salah satu hikmah yang dipahami sebagian masyarakat, bahwa puncak gunung Bawakaraèng adalah tempat bertemunya para Waliyullah yang dikenal dengan idiom Bugis: Walli Pituè (Wali tujuh) yang, konon, ini sebutan lain dari “Ashabul Kahfi” (penghuni gua).
Kesimpulan, Haji Bugis, Haji Bawakaraèng dan istilah ritual tradisi Islami lainnya penting dijelaskan makna semiotiknya di tengah masyarakat.
Ini dimaksudkan untuk membentengi pelaku tradisi dari tindakan penzaliman terhadap praktek budaya Islam.

Wallahu a’lamu bishawab.
Makassar, 21 Maret 2025